Mengenal Pajak Obesitas: Orang Gemuk Kena Pajak, Emang Boleh?
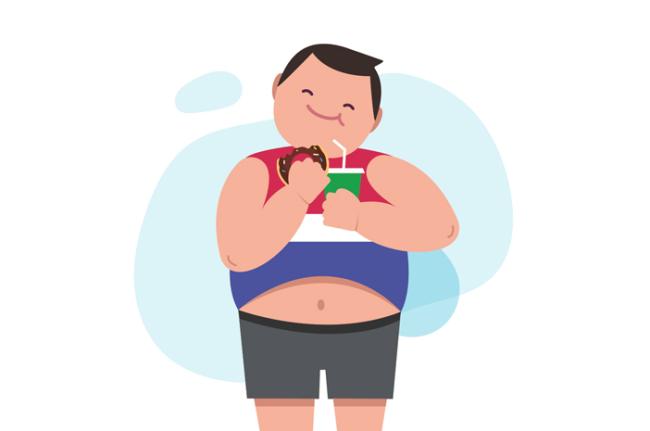
Oleh: Adi Fitnuril Widyatmoko, pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Di bangku sekolah kita tentu masih mengingat materi pelajaran sejarah tentang awal kemerdekaan Indonesia sampai pada akhir Pemerintahan Orde Lama dihadapkan dengan kondisi politik dan ekonomi yang sangat memprihantinkan. Pertempuran melawan agresi militer Belanda 1945-1949, banyaknya pemberontakan seperti PRRI/Permesta, NII, dan lain-lain, pertumbuhan ekonomi yang tergolong buruk bahkan sampai pada tingkat inflasi hampir 600%, serta kejadian G-30-S, menjadi daftar peristiwa yang mewarnai periode Orde Lama kala itu. Tidak bisa dibayangkan masa-masa sulit yang harus dihadapi masyarakat pada saat itu, yang mana untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan masih terasa sangat sulit.
Keadaan menjadi berubah ketika dimulainya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966. Kondisi politik dan keamanan menjadi lebih stabil, dan ditambah dengan investasi yang masuk ke Indonesia membuat hal tersebut berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Dengan ketersediaan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar, beberapa kebijakan zaman Orde Baru secara umum dapat dikatakan berhasil. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan pangan.
Program pembangunan infrastruktur pertanian seperti pembangunan bendungan dan waduk, pembangunan pabrik pupuk, subsidi pupuk dan benih, serta program pemerintah lainnya, menjadikan Indonesia waktu itu mencapai swasembada pangan. Terlepas dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan, dapat dipastikan bahwa kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat terpenuhi sehingga angka kelaparan menurun. Bahkan, sering kita dengar istilah guyonan, "Piye, penak jamanku, to?" (Bagaimana, enak zamanku, kan?)
Berlanjut pada zaman Reformasi, kita dapat menikmati taraf ekonomi masyarakat yang lebih baik. Hal ini menjadikan tingkat kebutuhan pangan semakin naik dan beragam. Urbanisasi dan modernisasi telah menyebabkan pergeseran preferensi makanan. Pola makan tradisional yang kaya sayuran dan biji-bijian telah digantikan oleh pola makan tinggi karbohidrat olahan, gula, dan lemak tidak sehat. Di samping itu, perilaku masyarakat dengan gaya hidup sedentari, seperti berjam-jam menatap gadget atau profesi di meja kerja, kian menjadi hal yang umum. Kondisi inilah yang juga menimbulkan semakin tingginya kasus obesitas di Indonesia.
Kasus obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang dialami banyak orang di dunia. Di Indonesia sendiri, angka obesitas meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Riset Kesehatan Dasar telah mencatat prevalensi obesitas (indeks massa tubuh >27) dari angka 10,5 pada tahun 2007 naik ke angka 21,8 pada tahun 2018. Selain itu, Obesitas di Indonesia juga berada pada peringkat ke-18 dari 108 negara yang terdata. Hal ini harus menjadi perhatian seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat sendiri, mengingat dampak dari obesitas cukup mengerikan bagi kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, nyeri sendi, penyakit jantung, dan berakhir dengan kematian.
Salah satu solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah pengenaan pajak obesitas. Wait, emang boleh? Penulis harus membuat penafian (disclaimer) bahwa tulisan ini bukan dimaksudkan untuk body shaming. Penulis semata-mata hendak mendiskusikan topik, bahwa ternyata ada, lho, negara yang menerapkan pajak obesitas.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penerapannya pajak terbagi dalam beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi stabilitas, fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi mengatur atau regulerend.
Selama ini kita mengetahui beberapa jenis pajak yang diterapkan di Indonesia seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan yang terakhir Pajak Karbon. Meskipun terkesan unik, nyatanya ada beberapa negara yang juga menerapkan kebijakan pengenaan pajak obesitas.
Otoritas Jepang telah mengeluarkan peraturan yang disebut sebagai Metabo Law atau Hukum Metabo. Dalam aturan tersebut diatur mengenai batas wajar berat badan melalui pengukuran lingkar pinggang. Lingkar pinggang laki-laki tidak boleh lebih dari 85 cm (kecuali atlet sumo), sedangkan untuk perempuan batas maksimal lingkar pinggangnya adalah 90 cm. Jika ada seseorang diketahui memiliki lingkar pinggang melebihi batas maksimal, maka akan dikenakan denda.
Dikutip dari news.ddtc.co.id, beberapa negara Eropa juga menerapkan apa yang disebut sebagai fat tax. Pemerintah Denmark sempat menerapkan fat tax mulai Oktober 2011, yang mana setiap jenis makanan yang diketahui mengandung lebih dari 2,3% lemak jenuh akan dikenakan biaya tambahan sebesar 3 US Dollar per kilogram. Namun setahun kemudian aturan tersebut dicabut karena banyak warganya yang pada akhirnya membeli barang makanan yang dikenakan fat tax lebih rendah di negara lain seperti Swedia atau Jerman.
Beberapa negara juga menunjukkan keberhasilan untuk menekan angka obesitas melalui pengenaan pajak atau cukai atas minuman manis. Meksiko, negara dengan konsumsi minuman soda tertinggi di dunia, menerapkan cukai sebesar satu peso per liter. Hasilnya, kebijakan ini berhasil menurunkan pembelian minuman soda sebesar 6% pada 2014 dan meningkat menjadi 7,6% di tahun berikutnya. Penerapan cukai 11% per liter pada minuman manis di Afrika Selatan tahun 2018 cukup berperan untuk menurunkan konsumsi minuman manis. Volume pembelian minuman manis yang awalnya mencapai 518-99 mL/hari menurun menjadi 492-16 mL/hari.
Dampak Positif
Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah aturan pajak obesitas atau pajak minuman manis dapat berpengaruh buruk terhadap ekonomi?
Riset yang bertajuk Business, Employment, and Productivity Impact of SSB Texas yang dirilis Bank Dunia (2020), justru menjelaskan sebaliknya. Dengan menggunakan sampel pajak Negara Bagian Illinois dan California, yang menggunakan modeling penerapan pajak sebesar 20%, hasil penelitian bahkan menunjukkan kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 0,06% di Illinois dan 0,03% di California.
Senada dengan studi yang susun oleh Lal, et.al. (2017) dengan judul Modelled Health Benefits of a Sugar-sweetened Beverage Tax Across Different Socioeconomic Groups in Australia: A Cost-effectiveness and Equity Analysis, hasil riset tersebut menyimpulkan bahwa pajak 20% minuman manis menghemat biaya perawatan kesehatan sebesar 1,735 juta dolar Australia dengan 49,5% dari total keuntungan kesehatan yang diperoleh dari dua kuantil terendah.
Bagi penulis, harus diakui bahwa kesadaran untuk menjaga kesehatan di masyarakat Indonesia masih rendah bahkan jika dengan dilakukan himbauan atau sosialisasi tentang bahaya obesitas. Sehingga perlunya upaya pemaksaan kepada masyarakat agar tujuan penurunan angka obesitas bisa tercapai. Pajak obesitas bisa menjadi salah satu solusi pemecah permasalahan tingginya angka obesitas yang tinggi di Indonesia.
Namun apakah ke depannya ide mengenai pajak obesitas ini akan benar-benar diterapkan di Indonesia? Tentunya hal ini harus dikaji terlebih dahulu oleh pemangku kepentingan, mengingat hal ini bisa saja menimbulkan pro-kontra bagi berbagai pihak khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 392 kali dilihat
