Prakarsa Indonesia Hijaukan Bumi Melalui Instrumen Ekonomi
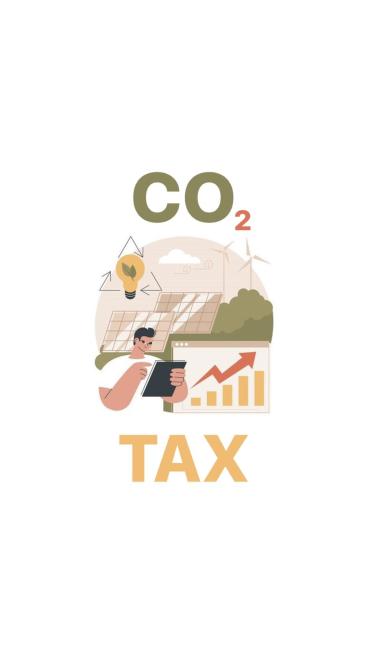
Oleh: Assyifa Anassafitri, pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Merosotnya kualitas lingkungan adalah masalah serius yang harus dihadapi seluruh manusia. Problem lingkungan seperti ketidakseimbangan ekologi, keterbatasan sumber daya, dan polusi telah menjadi masalah pelik di bidang ekonomi dan politik global karena berkaitan erat dengan perkembangan sosial dan keberlangsungan hidup manusia (Liu, dkk., 2020). Krugman (2010) menjelaskan bahwa jika masyarakat terus menjalankan bisnis seperti biasa, kita akan menghadapi kenaikan suhu global yang akan mencapai tingkat apokaliptik. Menurut data IQ Air, kualitas udara di Jakarta pada tahun 2023 telah mencapai predikat tidak sehat. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa degradasi sumber daya alam, sumber daya energi, dan lingkungan menjadi ancaman besar yang harus segera diatasi. Seluruh dunia berupaya dalam menemukan langkah untuk memulihkan dan memperbaiki alam, salah satunya adalah dengan menerapkan perekonomian hijau (green economy).
United Nations Environment Programme (UNEP) mengeluarkan Inisiatif Perekonomian Hijau atau yang dikenal dengan Green Economy Initiative (GEI) pada tahun 2008 yang terdiri dari penelitian global serta bantuan tingkat negara yang mendorong para pembuat kebijakan untuk mendukung investasi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. UNEP (2009) mendefinisikan perekonomian hijau sebagai sistem yang mengacu dalam proses infrastruktur dan konfigurasi ulang bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik atas modal sumber daya alam, ekonomi dan manusia, sekaligus menekan tingkat emisi gas rumah kaca, mengekstraksi dan mengeksploitasi lebih sedikit sumber daya alam, mengurangi kesenjangan sosial dan meminimalisir keluaran limbah.
Kasztelan & Armand (2017), sebagaimana dikutip dalam Indonesia Green Growth Program, menggambarkan bahwa hal utama munculnya perekonomian hijau sebagai bentuk langkah yang komprehensif untuk mengintegrasikan faktor lingkungan serta sosial dalam proses ekonomi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perekonomian hijau dibangun untuk melahirkan pertumbuhan ekonomi yang turut serta dalam pemanfaatan modal sumber daya alam yang akuntabel, mengurangi polusi, serta membuka peluang dalam meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Indonesia merupakan negara pemilik sumber daya alam yang melimpah jika dibandingkan dengan negara lain dalam hal gas bumi, minyak bumi, timah, batu bara, dan lain-lain. Konsekuensinya, kegiatan perekonomian di Indonesia sangat erat dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kementerian Keuangan telah membuat Strategi Perencanaan dan Penganggaran Hijau dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Green Planning and Budgeting/GPB) pada tahun 2015. Global Green Growth Institute (2015) menjelaskan, kendati GPB hanya mencakup kerangka waktu lima tahun, GPB menjadi fondasi yang kuat dalam kebijakan fiskal untuk mendorong strategi nasional jangka panjang dalam konteks perekonomian hijau.
Tata kelola perdagangan dan pajak karbon
Kementerian Keuangan telah melakukan upaya dalam mempercepat laju perubahan dalam implementasi perekonomian hijau di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah telah meluncurkan dua instrumen untuk menggunakan mekanisme pasar dalam mengakselerasi transformasi perekonomian hijau. Instrumen yang pertama adalah perdagangan, yaitu mekanisme perdagangan karbon dengan skema berbasis pasar yang memungkinkan perusahaan atau individu untuk berinvestasi dalam proyek lingkungan untuk menyeimbangkan jejak karbon mereka sendiri, atau yang lebih dikenal dengan mekanisme offsetting. Instrumen yang kedua adalah non-perdagangan, seperti halnya program yang bisa menurunkan karbondioksida (CO2) yaitu pajak karbon.
Glossary of Statistical Terms OECD menjelaskan bahwa pajak atas karbon merupakan instrumen internalisasi biaya lingkungan yang mana pajak karbon tersebut diartikan sebagai turunan dari Pigouvian tax, yaitu pajak yang dikenakan dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan dampak negatif yang memengaruhi kesejahteraan orang lain dan lingkungan. Penerapan pajak atas karbon menjadi bukti nyata pemerintah dalam implementasi green economy yang sudah diperkenalkan dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Terbitnya UU HPP menandai langkah awal bagi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim dan pencegahan pencemaran lingkungan. Meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu bumi perlu dikendalikan sehingga akan menurunkan kemungkinan bencana alam dan perubahan cuaca di Indonesia. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi aspek utama mengapa penerapan pajak karbon di Indonesia sangat diperlukan. Menurut World Research Institute (WRI), lebih dari setengah emisi gas rumah kaca global disumbang oleh sepuluh negara dunia, salah satunya adalah Indonesia (peringkat kelima) dengan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sebesar 965,3 MtCO2e atau setara 2% dari emisi dunia. Menurut UU HPP, tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Dalam gelaran Sustainability in Action Opportunities for a Better Tomorrow in Indonesia tahun ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pajak karbon menjadi salah satu indikator kuat untuk memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) dengan menurunkan emisi sebesar 31,89% sampai 43,20%, baik dengan upaya sendiri maupun kerja sama internasional pada tahun 2023.
Komitmen seluruh pihak
Dalam dokumen NDC, terdapat empat masalah utama. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen Indonesia dalam mematok target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% sampai dengan 41% di tahun 2030. Kebijakan pajak karbon dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi dan berkontribusi dalam pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut perlu dirancang secara khusus dengan tujuan untuk memaksimalkan sinergi dan manfaat jangka pendek, seperti pembukaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan efisiensi. Selama ini, kebijakan fiskal untuk implementasi perekonomian hijau masih terbatas pada area pengembangan opsi-opsi yang berfokus pada sektor energi dan penggunaan lahan. Dalam langkah selanjutnya, Kementerian Keuangan dapat mengembangkan kebijakan fiskal terutama dalam peraturan perpajakan untuk mendorong sektor industri menuju green electricity, green industry, dan green budgeting seperti dalam upaya menggerakan perekonomian yang rendah karbon dan mengupayakan subsidi kendaraan listrik secara optimal. Oleh karena itu, mulai dari masyarakat hingga pemerintah, perlu proaktif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan laju perubahan perekonomian hijau secara cepat dan tepat seiring dengan memperbaiki bumi dan lingkungannya.
*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 332 kali dilihat
