Dari Santri, oleh Santri, Bangkitkan Sadar Pajak untuk Negeri
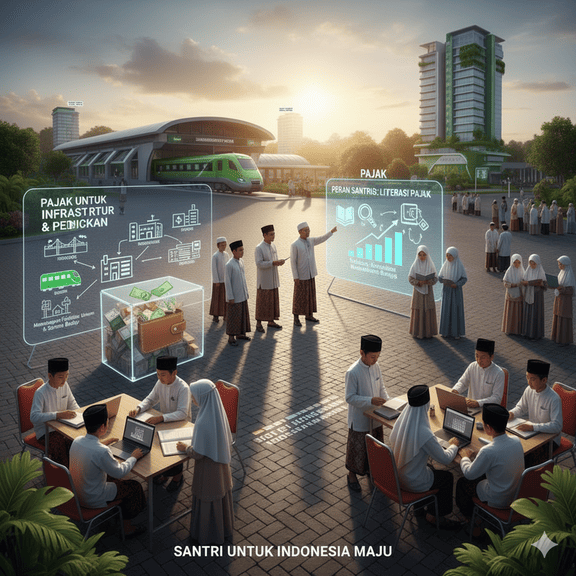
Oleh: (Eka Ardi Handoko), pegawai Direktorat Jenderal Pajak
"Hubbul wathon minal iman"
Ungkapan masyhur ini—Cinta tanah air adalah bagian dari iman—sering kali menggema di bilik-bilik pesantren dan majelis taklim. Bagi santri, loyalitas ganda antara ketaatan beragama dan kewajiban bernegara bukanlah paradoks, melainkan satu tarikan napas. Namun, sering kali, perwujudan cinta tanah air ini lebih banyak diterjemahkan dalam konteks spiritual, moral, dan seremonial.
Bagaimana jika "cinta tanah air" itu kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih membumi dan konkret? Bahasa yang mungkin terdengar asing di telinga sebagian kaum sarungan: bahasa pajak.
Selama ini, dunia pesantren dan pajak seolah berada di dua kutub magnet yang berbeda. Pesantren adalah simbol kesederhanaan, spiritualitas, dan pendidikan berbasis keikhlasan. Sementara itu, pajak adalah simbol administrasi negara yang modern, rumit, dan (sering dianggap) memberatkan.
Namun, di era modern ini, memisahkan keduanya adalah sebuah kekeliruan. Santri, sebagai salah satu pilar moral dan intelektual bangsa, tidak bisa lagi menutup mata terhadap instrumen fiskal yang menjadi tulang punggung negara ini.
Mengurai Mitos: Pesantren dan "Duniawi"
Ada stereotipe yang melekat bahwa santri hanya mengurusi “akhirat”. Mereka adalah ahli fikih, tafsir, dan tasawuf, tetapi gagap dalam urusan ekonomi modern, administrasi publik, atau perpajakan. Anggapan ini kian usang.
Faktanya, sejarah mencatat bagaimana para santri dan kiai berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Resolusi jihad yang dicetuskan Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari adalah bukti bahwa urusan negara adalah urusan santri. Mempertahankan kemerdekaan yang direbut dengan darah dan air mata itu hukumnya fardhu 'ain.
Di masa kini, "jihad" itu telah beralih bentuk. Jika dulu jihad adalah mengangkat senjata melawan penjajah, jihad hari ini adalah mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan tidak bisa diisi dengan perut kosong. Negara butuh "bensin" untuk bergerak. Bensin itu bernama anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang lebih dari 70%-nya disokong oleh pajak.
Jalan raya yang mulus untuk silaturahmi, subsidi listrik agar santri bisa mengaji di malam hari, beasiswa (seperti LPDP) yang mengirim ribuan santri belajar ke luar negeri, hingga gaji guru dan aparatur sipil negara—semuanya dibiayai oleh pajak.
Ironisnya, kesadaran ini seringkali absen dalam diskursus di pesantren. Pajak dianggap sebagai urusan "orang kota", "birokrat", atau "para pengusaha kakap". Padahal, setiap santri yang membeli kitab, sabun, atau pulsa, sejatinya telah ikut berkontribusi melalui pajak pertambahan nilai (PPN).
Era Baru: Santri sebagai Subjek Pajak
Persepsi bahwa santri dan kiai "kebal" pajak juga perlu diluruskan. Negara memang memberikan beberapa fasilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU PPh), sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib (seperti zakat) bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak.
Begitu pula, lembaga pendidikan seperti pesantren bisa dikecualikan dari PPh atas sisa lebih, asalkan dana tersebut ditanamkan kembali untuk pengembangan pendidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK-18/2021).
Namun, ini bukan berarti pesantren dan isinya steril dari pajak. Saat ini, pesantren tidak lagi hanya lembaga pendidikan murni. Ribuan pesantren telah bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Mereka memiliki koperasi (Kopontren), unit usaha air minum kemasan, peternakan lele, agrobisnis, hingga kafe dan minimarket.
Di sinilah peran santri modern diuji. Ketika seorang kiai atau pengurus pesantren mengelola bisnis, mereka memasuki ranah profesional. Bisnis tersebut, layaknya entitas bisnis lainnya, memiliki kewajiban perpajakan. Jika bisnis pesantren berkembang pesat tetapi abai dalam administrasi pajak, citra "jujur" dan "amanah" yang melekat pada pesantren justru bisa tercoreng.
Santri yang kini banyak terjun sebagai entrepreneur muda—baik itu di bidang fashion muslim, kuliner halal, atau startup digital—juga merupakan wajib pajak. Memahami cara menghitung PPh, kapan harus lapor surat pemberitahuan (SPT), dan apa hak serta kewajiban mereka, adalah sebuah keharusan. Ini bukan lagi pilihan, tapi kewajiban sebagai warga negara yang baik.
Menjadi Santri Agen Sadar Pajak
Lalu, apa yang bisa dilakukan santri? Perannya bisa lebih dari sekadar menjadi pembayar pajak yang patuh. Santri, dengan modal sosial dan keilmuan agamanya, bisa menjadi agen literasi pajak yang paling efektif.
1. Menjadi Jembatan Bahasa
Santri adalah "juru bicara" umat. Mereka terbiasa menerjemahkan konsep-konsep rumit (seperti ushul fiqh atau mantiq) ke dalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat awam. Tantangan yang sama berlaku untuk pajak.
Istilah seperti PPh Pasal 21, PPN, SPT Tahunan, atau tax amnesty terdengar sangat teknis. Santri bisa berperan dalam "membumikan" istilah ini. Misalnya, menjelaskan bahwa pajak adalah "iuran bersama" untuk membangun fasilitas umum, mirip dengan konsep urunan di kampung untuk memperbaiki jalan atau masjid.
2. Mengisi Mimbar Dakwah
Dakwah modern tidak melulu soal surga neraka. Dakwah bil hal (dengan perbuatan) adalah tentang solusi masalah sosial. Para dai muda dan santri bisa menyisipkan materi tentang pentingnya kejujuran (termasuk jujur dalam melaporkan penghasilan) dan gotong royong (termasuk gotong royong membayar pajak) dalam ceramah mereka.
Mereka bisa mengedukasi umat bahwa menghindari pajak (tax evasion) dengan cara yang ilegal, pada dasarnya sama dengan mengambil hak orang lain—hak fakir miskin atas subsidi, hak anak-anak atas sekolah gratis, dan hak publik atas layanan kesehatan yang layak.
3. Menjadi Pengawas yang Kritis
"Sadar pajak" bukan berarti patuh buta. Bagian terpenting dari hubbul wathon minal iman adalah memastikan amanah (dana pajak) itu digunakan dengan benar. Di sinilah intelektualitas santri berperan.
Santri harus menjadi kelompok yang paling vokal ketika korupsi dana pajak terjadi. Mereka harus mengawal APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketika mereka membayar pajak, mereka punya hak untuk bertanya, "Uang saya dipakai untuk apa?" Sikap kritis ini penting agar negara tidak zalim, dan uang umat benar-benar kembali untuk kemaslahatan umat.
Penutup
Era santri yang hanya berkutat di pesantren salaf sambil menjaga jarak dari "dunia luar" sudah berakhir. Santri hari ini adalah santri yang mengglobal, melek digital, dan paham isu-isu publik.
Memahami pajak adalah bagian dari menjadi santri yang kaffah (menyeluruh) di zaman modern. Ini adalah cara kita memastikan bahwa "cinta tanah air" tidak berhenti sebagai slogan di lisan, tetapi menjelma menjadi aksi nyata yang membangun peradaban.
Jika santri sudah melek pajak, mereka tidak hanya sedang mengamalkan ilmu fikih muamalah, tetapi juga sedang berinvestasi untuk masa depan Indonesia—negeri tempat mereka bersujud dan mengabdi.
*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 189 views
